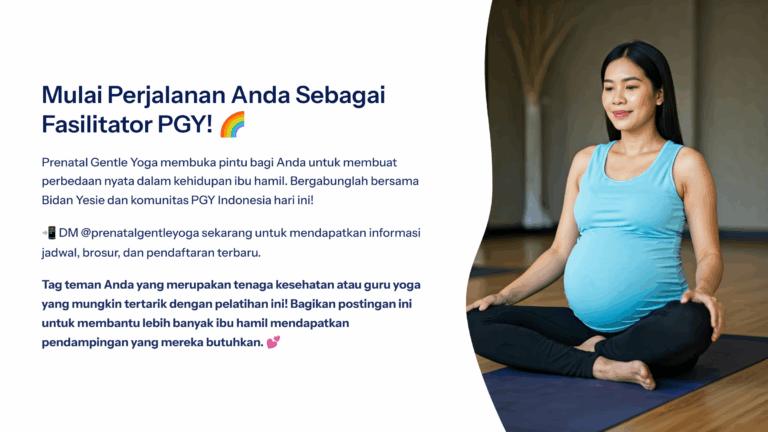DEMAM BERDARAH PADA KEHAMILAN
Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegepty dan Aedes albopictus dengan empat manifestasi klinis utama berupa demam tinggi, fenomena perdarahan, hepatomegali, dan pada kasus yang berat ditandai dengan kegagalan sirkulasi. Pasien dengan keadaan ini dapat berkembang menjadi syok hipovolemik karena adanya kebocoran plasma, yang dikenal dengan Dengue Shock Syndrome (DSS) yang berakibat fatal.
Epidemiologi
Di Indonesia DBD pertama kali dicurigai telah terjadi di Surabaya pada tahun 1968, tetapi konfirmasi virologis baru diperoleh pada tahun 1970. Di Jakarta, kasus pertama dilaporkan pada tahun 1969. Kemudian DBD berturut-turut dilaporkan di Bandung dan Jogjakarta (1972). Epidemi pertama di luar Jawa dilaporkan pada tahun 1972 di Sumatera Barat dan Lampung, disusul oleh Riau, Sulawesi Utara dan Bali (1973). Pada tahun 1974, epidemi dilaporkan di Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 1994 DBD telah menyebar ke seluruh propinsi di Indonesia. Pada saat ini DBD sudah endemis di banyak kota besar, bahkan sejak tahun 1975 penyakit ini telah terjangkit di pedesaan.
Berdasarkan jumlah kasus DBD, Indonesia menempati urutan kedua setelah Thailand. Sejak tahun 1968 angka kesakitan rata-rata DBD di Indonesia terus meningkat dari 0,05 (1968) menjadi 8,14 (1973) menjadi 8,65 (1983) dan mencapai angka tertinggi pada tahun 1988 yaitu 27,09 per 100.000 penduduk dengan penderita sebanyak 57.573 orang, dengan 1.527 orang penderita dilaporkan meninggal dari 201 daerah tingkat II.
Morbiditas dan mortalitas DBD yang dilaporkan berbagai negara bervariasi disebabkan beberapa faktor antara lain status umur penduduk, kepadatan vektor, tingkat penyebaran virus dengue, prevalensi serotipe virus dengue dengan kondisi metereologis.
Pada awal terjadinya wabah di suatu negara, distribusi umur penderita memperlihatkan jumlah penderita terbanyak dari golongan anak berumur kurang dari 15 tahun (86-95%). Namun, pada wabah-wabah selanjutnya, jumlah penderita yang digolongkan dalam usia dewasa muda meningkat.
Di Indonesia virus DEN-1, DEN-2, DEN-3, dan DEN-4 telah berhasil diisolasi dari darah penderita. Di Jakarta daerah endemis tinggi, dari sebagian besar penderita DBD derajat berat maupun yang meninggal dapat diisolasi virus DEN-3. Survei virologis penderita DBD telah dilekukan di beberapa rumah sakit di Indonesia sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 1995. Keempat serotipe virus dengue berhasil diisolasi baik dari penderita DBD derajat ringan maupun berat. Selama 17 tahun, serotipe yang berdominasi adalah virus dengue serotipe DEN-2 atau DEN-3
Laporan kepustakaan mengenai demam berdarah dengue dalam kehamilan dan persalinan masih sangat sedikit. Penelitian di Haiti dan Republik Dominika melaporkan bahwa setengah dari semua anak yang telah mencapai usia 2 tahun di negara tersebut mempunyai antibodi terhadap dengue. Pada saat periode non epidemik, surveilens di Republik Dominika terhadap darah dari 54 ibu hamil dan darah tali pusat bayi yang dilahirkannya menunjukkan bahwa attack rate adalah 6%. Dilaporkan pula bahwa kadar antibodi di dalam darah tali pusat lebih tinggi daripada di dalam darah ibu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam kehamilan telah terjadi imunisasi pasif transplasental.
Etiologi
Demam Berdarah Dengue (DBD) disebabkan oleh virus dengue yang termasuk kelompok B Arthropod Borne Virus (Arbovirus) dan sekarang dikenal sebagai genus Flavivirus, famili Flaviviridae, yang memiliki 4 jenis serotipe yaitu DEN-1, DEN-2, DEN-3, dan DEN-4. Infeksi oleh salah satu serotipe akan menimbulkan antibodi terhadap serotipe yang bersangkutan, sedangkan antibodi yang terbentuk terhadap serotipe yang lain sangat kurang, sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap serotipe lain tersebut.
Patofisiologi
Patofisiologi primer DBD dan DSS adalah peningkatan akut permeabilitas vaskuler yang mengarah pada kebocoran plasma ke dalam ruang ekstravaskuler, sehingga meningmbulkan hemokonsentrasi dan penurunan tekanan darah. Volume plasme menurun lebih dari 20% pada kasus-kasus berat, hal ini didukung oleh penemuan post-mortem meliputi efusi serosa, efusi pleura, hemokonsentrasi dan hipoproteinemia.
Tidak terjadi lesi destruktif yang nyata pada vaskuler, menunjukkan bahwa perubahan sementara fungsi vaskuler diakibatkan suatu mediator kerja singkat. Jika penderita sudah stabil dan mulai sembuh, cairan ekstravasasi diarborbsi dengan cepat, menimbulkan penurunan hematokrit. Perubahan hemostasis pada DBD dan DSS melibatkan 3 faktor yaitu perubahan vaskuler, trombositopenia, dan kelainan koagulasi. Hampir semua penderita DBD mengalami peningkatan fragilitas vaskuler dan trombositopenia, dan banyak di antaranya penderita menunjukkan hasil pemeriksaan koagulasi yang abnormal.
Patogenesis
Virus dengue masuk ke dalam tubuh manusia lewat gigitan nyamuk Aedes aegepty atau Aedes albopictus. Organ sasaran dari virus ini adalah organ hepar, nodus limfaticus, sumsum tulang serta paru-paru. Data dari perbagai penelitian menunjukkan bahwa sel-sel monosit dan makrofag mempunyai peranan besar pada infeksi ini. Dalam peredaran darah, virus tersebut akan difagosit oleh sel monosit perifer.
Virus DEN mampu bertahan hidup dan mengadakan multifikasi di dalam sel tersebut. Infeksi virus dengue mulai dengan menempelnya virus genomnya masuk ke dalam sel dengan bantuan organel-organel sel, genom virus membentuk komponen-komponennya, baik komponen antara maupun komponen struktural virus. Setelah komponen struktural dirakit, virus dilepaskan dari dalam sel. Proses perkembangbiakan virus DEN terjadi di sitoplasma sel.
Semua Flavivirus memiliki kelompok epitop pada selubung protein yang menimbulkan reaksi silang pada uji serologis. Hal ini menyebabkan diagnosis pasti dengan uji serologi sulit ditegakkan. Kesulitan ini dapat terjadi di antara keempat serotipe virus DEN. Infeksi oleh satu serotipe virus DEN menimbulkan imunitas protektif terhadap serotip virus tersebut, tetapi tidak ada proteksi silang terhadap serotipe virus yang lain.
Patogenesa DBD dan DSS masih merupakan masalah yang kontroversial. Dua teori yang banyak dianut pada DBD dan DSS adalah hipotesis infeksi sekunder (secondary heterologous infection theory) atau hipotesis immune enchancement. Hipotesis ini menyatakan secara tidak langsung bahwa pasien yang mengalami infeksi yang kedua kalinya dengan serotipe virus dengue yang heterolog, mempunyai risiko yang lebih besar untuk menderita DBD atau DSS. Antibodi heterolog yang telah ada sebelumnya akan mengenai virus lain yang akan menginfeksi dan kemudian membentuk kompleks antigen antibodi yang kemudian berikatan dengan faktor reseptor dari membran sel leukosit terutama makrofag. Oleh karena antibodi heterolog maka virus tidak dinetralisasikan oleh tubuh sehingga akan bebas melakukan replikasi dalam sel makrofag. Dihipotesiskan juga mengenai antibody dependent enchancement (ADE), suatu proses yang akan meningkatkan infeksi dan replikasi virus dengue di dalam sel mononuklear. Sebagai tanggapan terhadap infeksi tersebut, terjadi sekresi mediator vasoaktif yang kemudian menyebabkan peningkatan permeabilitas pembuluh darah, sehingga mengakibatkan keadaan hipovolemia dan syok.
Patogenesis terjadinya syok berdasarkan hipotesis the secondary heterologous infection theory yang dirumuskan oleh Suvatte tahun 1977. Sebagai akibat infeksi sekunder oleh tipe virus dengue yang berlainan pada seorang pasien, respon antibodi anamnestik yang akan terjadi dalam waktu beberapa hari mengakibatkan proliferasi dan transformasi limfosit dengan menghasilkan titer tinggi antibodi IgG anti dengue. Di samping itu, replikasi virus dengue terjadi juga dalam limfosit yang bertransformasi dengan akibat terdapatnya virus dalam jumlah banyak. Hal ini akan mengakibatkan terbentuknya kompleks antigen antibodi (virus antibody complex) yang selanjutnya akan mengakibatkan aktivasi sistem komplemen. Pelepasan C3a dan C5a akibat aktivasi C3 dan C5 menyebabkan peningkatan permeabilitas dinding pembuluh darah dan merembesnya plasma dari ruang intravaskuler ke ruang ekstravaskuler. Pada pasien dengan syok berat, volume plasma dapat berkurang sampai lebih dari 30% dan berlangsung selama 24-43 jam. Perembesan plasma ini terbukti dengan adanya peningkatan kadar hematokrit, penurunan kadar natrium, dan terdapatnya cairan di dalam rongga serosa (efusi pleura, ascites). Syok yang tidak ditanggulangi secara adekuat akan menyebabkan asidosis dan anoksia, yang dapat berakhir fatal, oleh karena itu pengobatan syok sangat penting guna mencegah kematian.
Hipotesis kedua menyatakan bahwa virus dengue seperti juga virus binatang lain, dapat mengalami perubahan genetik akibat tekanan sewaktu virus mengadakan replikasi baik pada tubuh manusia maupun pada tubuh nyamuk. Ekspresi fenotipik dari perubahan genetik dalam genom virus dapat menyebabkan peningkatan replikasi virus dan viremia, peningkatan virulensi, dan mempunyai potensi untuk menimbulkan wabah yang besar. Kedua hipotesis tersebut didukung oleh data epidemiologis dan laboratoris.
Sebagai tanggapan terhadap infeksi virus dengue, kompleks antigen antibodi selain mengaktivasi sistem komplemen, juga menyebabkan agregasi trombosit dan mengaktivasi sistem koagulasi melalui kerusakan sel endotel pembuluh darah. Kedua faktor tersebut akan menyebabkan perdarahan pada DBD. Agregasi trombosit terjadi sebagai akibat dari perlekatan kompleks antigen antibodi pada membran trombosit mengakibatkan pengeluaran ADP (adenosin di phospat) sehingga trombosit mekekat satu sama lain. Hal ini akan menyebabkan trombosit dihancurkan oleh RES (reticulo endothelial system) sehingga terjadi trombositopenia. Agregasi trombosit ini akan menyebabkan pengeluaran platelet faktor III mengakibatkan terjadinya koagulopati konsumtif (KID=koagulasi intravaskuler diseminata), ditandai dengan peningkatan FDP (fibrinogen degredation product) sehingga terjadi penurunan faktor pembekuan.
Agregasi trombosit ini juga mengakibatkan gangguan fungsi trombosit sehingga walaupun jumlah trombosit masih cukup banyak, tidak berfungsi baik. Di sisi lain, aktivasi koagulasi akan menyebabkan aktivasi faktor Hageman sehingga terjadi aktivasi sistem kinin sehingga memacu peningkatan permeabilitas kapiler yang dapat mempercepat terjadinya syok. Jadi, perdarahan masif pada DBD diakibatkan oleh trombositopenia, penurunan faktor pembekuan (akibat KID), kelainan fungsi trombosit, dan kerusakan dinding endotel kapiler. Akibatnya, perdarahan akan memperberat syok yang terjadi.
Gangguan Hemostasis Pada Demam Berdarah Dengue
Infeksi virus dengue dapat asimtomatik atau disertai manifestasi klinis berupa demam tidak terdiferensiasi, demam dengue atau demam berdarah dengue. Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan manifestasi infeksi virus dengue yang berat yang ditandai dengan terjadinya perembesan plasma dan gangguan hemostasis sehingga berpotensi menimbulkan syok (Dengue Shock Syndrome). Gangguan hemostasis pada demam berdarah dengue dapat berupa vaskulopati, trombositopenia, gangguan fungsi trombosit, koagulopati dan Koagulasi Intravaskular Diseminata (KID).
Proses imunopatologi yang terjadi pada demam berdarah dengue melibatkan sistem imunitas humoral dan selular. Hipotesis secondary heterologous infection oleh Halstead menyatakan reaksi antibodi terhadap virus dari infeksi sebelumnya akan mempermudah infeksi virus terhadap monosit dan makrofag (antibody dependent enhancement). Disamping hipotesis tersebut diketahui pula peran komplemen, limfosit T dan berbagai mediator seperti TNF-a, IL-2, IL-6, IFN-g, PAF, C3a, C5a dan histamin yang menyebabkan disfungsi endotel, perembesan plasma, renjatan, gangguan koagulasi dan manifestasi perdarahan Peran IL-18 terhadap diferensiasi sel T menjadi T-helper 1 diperkirakan juga berperan dalam patogenesis demam berdarah dengue.
Vaskulopati bermanifestasi sebagai uji 1 touniquet yang positif dan petekie yang terjadi pada awal demam sebelum terjadinya, trombositopenia. Gangguan vaskular yang terjadi berupa infiltrasi dinding vaskular oleh limfosit fagosit mononuklear, deposit IgM, komplemen dan fibrinogen. Vaskulopati terjadi sebagai akibat pengaruh virus secara langsung saat awal infeksi atau sebagai akibat reaksi imunologis yang terjadi saat konvalesen.
Trombositopenia dengan jumlah trombosit £ 100.000/ mm3 terjadi pada hari ke 3-7 demam dan kembali meningkat pada hari ke 8-9. Jumlah trombosit pada syok (DSS) pada umumnya £ 50.000/mm3 dengan rata-rata 20.000/mm3. Perdarahan umumnya tidak terjadi walaupun jumlah trombosit £ 20.000/mm3 kecuali pada keadaan syok berkepanjangan (prolonged shock). Trombositopenia pada infeksi dengue terjadi melalui mekanisme:
1. Supresi sumsum tulang
2. Destruksi dan pemendekan masa hidup trombosit.
Gambaran sumsum tulang pada fase awal infeksi (< 5 hari) menunjukkan keadaan hiposeluler dan supresi megakariosit. Setelah keadaan nadir tercapai akan terjadi peningkatan proses hematopoiesis termasuk megakariopoiesis. Kadar trombopoietin dalam darah pada saat terjadi trombositopenia justru menunjukkan kenaikan, hal ini menunjukkan terjadinya stimulasi trombopoiesis sebagai mekanisme kompensasi terhadap keadaan trombositopenia. Destruksi trombosit terjadi melalui pengikatan frogmen C3g, karena terdapatnya antibodi VD, konsumsi trombosit selama proses koagulopati dan sekuestrasi di perifer. Gangguan fungsi trombosit terjadi melalui mekanisme gangguan pelepasan ADP, peningkatan kadar B-tromboglobulin dan PF4 yang merupakan petanda degranulasi trombosit.
Koagulopati terjadi pada berbagai infeksi virus dan bakteri termasuk infeksi virus dengue. Koagulopati terjadi sebagai akibat interaksi virus dengan endotel yang menyebabkan disfungsi endotel. Berbagai penelitian menunjukkan terjadinya koagulopati konsumtif pada demam berdarah dengue derajat III dan IV. Terjadi pemanjangan masa protombin (PT), masa tromboplasin parsial teraktivasi (APTT), penurunan fibrinogen dan peningkatan D-Dimer atau FDP, serta penurunan berbagai faktor koagulasi (11, V, VII, VIII, IX, X dan XII). Aktivasi koagulasi pada demam berdarah dengue seperti juga pada sepsis diperkirakan melalui jalur ekstrinsik (tissue factor pathway). Jalur intrinsik juga berperan melalui aktivasi faktor XIa namun tidak melalui, aktivasi kontak (kalikrein C1-inhibitor complex). Aktivitas antitrombin III pada demam berdarah dengue menurun terutama pada DSS dan berkorelasi dengan PT, APTT, kadar albumin dan fibrinogen. Proses koagulopati yang berlangsung di luar batas kompensasi menyebabkan terjadinya penumpukan fibrin, KID dan kegagalan organ multipel.
Bagaimana pengaruh gangguan hemostasis/koagulasi terhadap risiko perdarahan dan mortalitas pada pasien DBD dan DSS, kiranya masih memerlukan penelitian lebih lanjut; walaupun pada DBD derajat I pada umumnya dapat membaik tanpa memerlukan intervensi terapi. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa gangguan hemostasis pada demam berdarah dengue merupakan proses kompleks yang melibatkan fungsi vaskuler, trombosit dan koagulasi dan terkait dengan keadaan klinis dan derajat penyakit.
Manifestasi Klinis
Infeksi virus dengue tergantung dari faktor yang mempengaruhi daya tahan tubuh dengan faktor-faktor yang mempengaruhi virulensi virus. Dengan demikian infeksi virus dengue dapat menyebabkan keadaan yang bermacam-macam, mulai dari tanpa gejala (asimptomatik), demam ringan yang tidak spesifik, demam dengue, atau bentuk yang lebih berat yaitu demam berdarah dengue (DBD) dan Dengue Shock Syndrome (DSS).
1. Demam dengue (DD)
Bentuk klasik demam dengue adalah gejala demam tinggi mendadak, kadang-kadang bifasik (saddle back fever), nyeri kepala berat, nyeri belakang bola mata, nyeri otot, tulang atau sendi, mual, muntah, dan timbulnya ruam-ruam di kulit. Ruam berbentuk makulopapular yang bisa timbul pada awal penyakit dapat menghilang namun timbul kembali pada hari ke 6 atau ke 7 terutama di daerah kaki, tangan, dan telapak kaki atau tangan. Kadang-kadang ditemui keadaan trombositopenia dan leukopenia. Masa penyembuhan dapat disertai rasa lesu yang berkepanjangan.
2. Demam Berdarah Dengue (DBD)
Bentuk klasik DBD ditandai dengan demam tinggi, mendadak 2-7 hari, disertai dengan muka kemerahan. Keluhan seperti anoreksia, sakit kepala, nyeri otot, tulang, sendi, mual, dan muntah sering ditemukan. Beberapa penderita mengeluh nyeri menelan dengan farings hiperemis ditemukan pada pemeriksaan, namun jarang ditemukan batuk pilek. Nyeri epigastrium dan di bawah tulang iga kanan, serta nyeri di daerah perut yang bersifat umum, biasa ditemukan. Demam tinggi dapat menimbulkan kejang demam terutama pada bayi.
Bentuk perdarahan yang paling sering ditemukan adalah uji tourniquet (rumple leed) positif, kulit mudah memar dan perdarahan pada bekas suntikan intravena atau pada bekas pengambilan darah. Pada kebanyakan kasus petekia halus ditemukan tersebar di daerah ekstremitas, aksila, wajah, dan palatum mole, yang biasanya ditemukan pada fase awal dari demam. Epistaksis dan perdarahan gusi lebih jarang ditemukan, perdarahan saluran cerna ringan dapat ditemukan pada fase demam. Keadaan hepatomegali juga dapat ditemukan.
Masa kritis dari penyakit terjadi pada fase akhir demam, pada saat ini penurunan suhu yang tiba-tiba sering disertai dengan gangguan sirkulasi yang bervariasi dalam berat-ringannya. Pada kasus dengan gangguan sirkulasi ringan, perubahan yang terjadi minimal dan sementara, pada kasus berat penderita dapat mengalami syok.
DBD dibedakan dari DD dengan adanya kebocoran plasma yang bermanifestasi sebagai peningkatan nilai hematokrit, efusi pada rongga pleura atau rongga peritoneum, atau hipoproteinemia. Perjalanan penyakit dapat dipengaruhi oleh diagnosis dini dan pemberian cairan.
Berdasarkan manifestasi klinis yang ditemukan, DBD dibagi atas 4 derajat, yaitu:
Derajat I :Demam disertai gejala tidak khas dan satu-satunya manifestasi perdarahan ialah uji tourniquet.
Derajat II :Seperti derajat 1, disertai perdarahan spontan di kulit dan/atau perdarahan lain.
Derajat III :Kegagalan sirkulasi yang ditandai dengan denyut nadi yang cepat dan lemah, tekanan nadi menurun (20 mmHg atau kurang), atau  hipotensi, ditandai dengan kulit dingin dan lembab serta pasien menjadi gelisah.
Derajat IV :Syok berat, nadi tidak teraba dan tekanan darah tidak terukur.
Diagnosis
Perubahan patofisiologi pada infeksi dengue menentukan perbedaan perjalanan penyakit antara DBD dengan DD. Perubahan patofisiologis tersebut adalah kelainan hemostasis dan perembesan plasma. Kedua kelainan tersebut dapat diketahui dengan adanya trombositopenia dan peningkatan hematokrit. Oleh karena itu, trombositopenia dan hemokonsentrasi merupakan kejadian yang selalui dijumpai.
Diagnosis DBD ditegakkan berdasarkan kriteria diagnosis menurut WHO tahun 1997 yang terdiri dari kriteria klinis dan laboratoris.
Kriteria klinis:
Demam tinggi mendadak tanpa diketahui penyebab yang jelas dan berlangsung terus menerus selama 2-7 hari. Terdapat manifestasi perdarahan ditandai dengan:
a. Uji tourniquet positif
b. Ptekie, ekimosis, purpura
c. Perdarahan mukosa, epistaksis, perdarahan gusi
d. Hematemesis dan atau melena
Pembesaran hati Syok, ditandai nadi cepat dan lemah serta penurunan tekanan nadi, kaki dan tangan dingin, kulit lembab, dan pasien tampak gelisah.
Kriteria Laboratoris adalah:
Trombositopenia (100.000/mm3 atau kurang) Hemokonsentrasi, peningkatan hematokrit 20% atau lebih
Dua kriteria klinis pertama ditambah trombositopenia dan hemokonsentrasi atau peningkatan hematokrit cukup untuk menegakkan diagnosis klinis DBD. Efusi pleura dan atau hipoalbuminemia dapat memperkuat diagnosis terutama pada pasien anemia dan atau terjadi perdarahan. Pada kasus syok, peningkatan hematokrit dan adanya trombositopenia mendukung diagnosis DBD.
Diagnosis Laboratoris
Diagnosis defenitif infeksi virus dengue hanya dapat dilakukan di laboratorium dengan cara isolasi virus, deteksi antigen virus atau RNA dalam serum atau jaringan tubuh, dan deteksi antibodi spesifik dalam serum pasien.
Diagnosis Serologis
Dikenal 5 jenis uji serologis yang biasa dipakai untuk menentukan adanya infeksi virus dengue, yaitu:
Uji hemaglutinasi inhibisi
Uji hemaglutinasi inhibisi adalah uji serologis yang dianjurkan dan paling sering dipakai dan dipergunakan sebagai gold standard pada pemeriksaan serologis.
Uji komplemen
Uji komplemen fiksasi jarang dipergunakan sebagai uji diagnostik secara rutin, oleh karena selain cara pemeriksaan agak rumit prosedurnya juga memerlukan tenaga pemeriksa yang berpengalaman. Berbeda dengan antibodi HI, antibodi komplemen fiksasi hanya bertahan beberapa tahun saja (sekitar 2-3 tahun).
Uji neutralisasi
Uji neutralisasi adalah uji serologi yang paling spesifik dan sensitif untuk virus dengue. Biasanya uji neutralisasi memakai cara yang disebut Plaque Reduction Neutralization Test (PRNT) yaitu berdasarkan adanya reduksi dari plaque yang terjadi. Saat antibodi neutralisasi dapat dideteksi dalam serum hampir bersamaan dengan HI antibodi tetapi lebih cepat dari antibodi komplemen fiksasi dan bertahan lama (>4-8 tahun). Uji ini juga rumit dan memerlukan waktu yang cukup lama sehingga tidak dipakai secara rutin.
IgM Elisa
Uji ini pada tahun terakhir merupakan uji serologi yang banyak dipakai. Uji ini mempunyai sensitifitas sedikit di bawah uji HI, dengan kelebihan yaitu hanya memerlukan satu serum akut saja dengan spesifisitas yang sama dengan uji HI.
IgG Elisa
Uji IgG Elisa sebanding dengan uji HI, hanya sedikit lebih spesifik.
Diagnosis banding
Etiologi demam pada awal penyakit umumnya sulit diketahui, karenanya perlu ditelit infeksi pada alat-alat tubuh baik yang disebabkan bakteri maupun virus, seperti bronkopneumonia, kolesistitis, pielonefritis, demam tifoid, malaria dan sebagainya. Adanya ruam yang akut seperti pada morbili perlu dibedakan dengan DBD. Biasanya pada morbili ruamnya lebih banyak, adanya bintik-bintik koplik pada selaput lendir mulut dan selalu ditemukan koriza. Adanya pembesaran hati perlu dibedakan dengan hepatitis akut dan leptospirosis. Pada hari ke 3-4 demam dengan adanya manifestasi perdarahan, kemungkinan diagnosis DBD akan lebih besar.
Perdarahan di kulit seperti petekie dan kimosis ditemukan pada beberapa penyakit infeksi, misalnya sepsis, meningitis, meningokokus. Pada sepsis, sejak semula pasien tampak sakit berat, demam naik turun, dan ditemukan tanda-tanda infeksi. Di samping itu jelas terdapat leukositosis disertai dominasi sel polimorfonuklear. Pemeriksaan laju endap darah (LED) dapat dipergunakan untuk membedakan infeksi bakteri dengan virus. Pada meningitis meningokokus jelas terdapat tanda rangsangan meningeal dan kelainan pada pemeriksaan cairan serebrospinalis.
Penyakit-penyakit darah seperti idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP), leukemia pada stadium lanjut dan anemia aplastik dapat pula memberikan gejala-gejala yang mirip DBD. Pemeriksaan sumsum tulang akan dapat memberi kepastian mengenai diagnosis.
Renjatan endotoksik dan renjatan karena dengue sulit dibedakan. Umur, faktor predisposisi dan perjalanan klinisnya dapat membantu membedakannya.
Gejala penyakit yang disebabkan virus Chikungunya (juga suatu arbovirus) mirip sekali dengan dengue, terutama mengenai lama demam dan manifestasi perdarahan, tetapi tidak pernah menyebabkan renjatan dan gangguan kesadaran.
Komplikasi
1. Ensefalopati Dengue
Pada umumnya ensefalopati terjadi sebagai komplikasi syok yang berkepanjangan dengan perdarahan, tetapi dapat juga terjadi pada DBD yang tidak disertai syok. Gangguan metabolik seperti hipoksemia, hiponatremia, atau perdarahan, dapat menjadi penyebab terjadinya ensefalopati. Melihat ensefalopati DBD bersifat sementara, maka kemungkinan dapat juga disebabkan oleh trombosis pembuluh darah otak sementara sebagai akibat dari koagulasi intravaskular diseminata (KID).
2. Kelainan Ginjal
Gagal ginjal akut pada umumnya terjadi pada fase terminal, sebagai akibat dari syok yang tidak teratasi dengan baik.
3. Edema Paru
Edema paru adalah komplikasi yang mungkin terjadi sebagai akibat berlebihan pemberian cairan. Pemberian cairan pada hari ketiga sampai kelima sesuai panduan yang diberikan, biasanya tidak akan menyebabkan edema paru oleh karena perembesan plasma masih terjadi. Akan tetapi apabila pada saat terjadi reabsorbsi plasma dari ruang ekstra, apabila cairan masih diberikan (kesalahan terjadi bila hanya melihat penurunan kadar hemoglobin dan hematokrit tanpa memperhatikan hari sakit) pasien akan mengalami distres pernafasan, disertai sembab pada kelopak mata, dan tampak adanya gambaran edema paru pada foto dada.
Prognosis
Kematian oleh demam dengue hampir tidak ada, sebaliknya pada DBD atau DSS mortalitasnya cukup tinggi.
Pencegahan
Untuk memutuskan rantai penularan, pemberantasan vektor dianggap cara paling memadai saat ini. Vektor dengue khususnya A.aegypti sebenarnya mudah diberantas karena sarang-sarangnya terbatas di tempat yang berisi air bersih dan jarak terbangnya maksimum 100 meter. Tetapi karena vektor terbesar luas, untuk keberhasilan pemberantasan diperlukan total coverage (meliputi seluruh wilayah) agar nyamuk tak dapat berkembang biak lagi. Terdapat 2 cara pemberantasan vektor:
1. Menggunakan insektisida.
Yang lazim dipakai dalam program pemberantasan demam berdarah dengue adalah malathion untuk membunuh nyamuk dewasa (adultisida) dan temephos (abate) untuk membunuh jentik (larvasida). Cara penggunaan malathion ialah dengan pengasapan (thermal fogging) atau pengabutan (cold fogging). Untuk pemakaian rumah tangga dapat digunakan berbagai jenis insektisida yang disemprotkan di dalam kamar/ruangan, misalnya golongan organofosfat, karbamat atau pyrethroid. Cara penggunaan temephos (abate) ialah dengan pasir abate (sand granules) ke dalam sarang-sarang nyamuk aedes, yaitu bejana tempat penampungan air bersih. Dosis yang digunakan ialah 1 ppm atau 1 gram Abate SG 1 % per 10 liter air.
2. Tanpa insektisida
Caranya adalah:
a. Menguras bak mandi, tempayan dan tempat penampungan air minimal 1x seminggu (perkembangan telur ke nyamuk lamanya 7-10 hari.
b. Menutup tempat penampungan air rapat-rapat.
c. Membersihkan halaman rumah dari kaleng-kaleng bekas, botol-botol pecah dan benda lain yang memungkinkan nyamuk bersarang.
Isolasi pasien agar pasien tidak digigit vektor untuk ditularkan kepada orang lain sulit dilaksanakan lebih awal dari perawatan di rumah sakit karena kesulitan praktis. Mencegah gigitan nyamuk dengan cara memakai obat gosok maupun pemakaian kelambu memang dapat mencegah gigitan nyamuk, tetapi cara ini dianggap kurang praktis. Imunisasi maupun pemberian anti-virus dalam usaha memutuskan rantai penularan, saat ini baru dalam taraf penelitian.
Dampak Infeksi Virus Dengue Pada Kehamilan
Wanita hamil harus berhati-hati pada infeksi virus dengue, karena infeksi yang terjadi mungkin dapat mempengaruhi janin. Demam dengue pada wanita hamil tidak menyebabkan abnormalitas pada janin tetapi dapat berisiko terjadi kematian janin. Janin yang dilahirkan dapat menderita kegagalan multiorgan pada saat lahir.
Ada beberapa laporan kasus transmisi vertikal virus dengue. Salah satunya pada wanita Thailand dengan sakit panas yang melahirkan bayinya melalui seksio sesarea. Meski virus dengue tidak dapat diisolasi dari si ibu, namun data serologi menunjukkan dengue sebagai penyebab panas pada ibu tersebut. Bayi yang dilahirkan menderita pireksia pada umur 6 hari dan hal ini mungkin dikarenakan si bayi mendapat infeksi virus dengue dari ibunya, meskipun ada kemungkinan si bayi digigit nyamuk pada umur 1 atau 2 hari. Selain itu, pada kasus yang lain dilaporkan bayi yang dilahirkan dari seorang wanita yang menderita DBD pada waktu hamil menderita panas pada umur 48 jam. Bayi ini menderita panas selama 2 hari, hepatomegali, trombositopenia, dan efusi pleura. Dengan menggunakan PCR (polymerase chain reaction) terdeteksi virus dengue tipe 1 di serumnya.
PENATALAKSANAAN DEMAM BERDARAH DENGUE
Tidak ada pengobatan yang spesifik untuk DD dan DBD karena infeksi virus ini adalah self limited. Pengobatan dengue fever tanpa komplikasi mencakup terapi suportif dan meliputi penghilangan rasa nyeri, penurunan temperatur tubuh, tirah baring, dan pemberian cairan.
Pada beberapa kasus yang meragukan diperlukan observasi dan pemeriksaan lanjut dan penderita dapat dirawat di rumah sakit apabila:
DBD dengan syok dengan atau tanpa perdarahan DBD dengan perdarahan masih dengan atau tanpa syok DBD tanpa perdarahan masif dengan: Hb, Ht normal dengan trombositopenia < 100.000/µl Hb, Ht yang meningkat dengan trombositopenia < 150.000/µl
Pasien yang dicurigai menderita DBD dengan hasil pemeriksaan Hb, Ht, dan trombosit dalam batas normal dapat dipulangkan dengan anjuran kembali kontrol ke poliklinik dalam waktu 24 jam berikutnya atau apabila keadaan pasien memburuk.
1. Penatalaksanaan DBD tanpa perdarahan masif dan syok
Pada pasien DBD tanpa perdarahan masif dan syok di ruang rawat, cairan Ringer Laktat merupakan pilihan pertama. Cairan lain yang dapat digunakan antara lain adalah cairan Dextrosa 5% dalam Ringer Laktat atau Ringer Asetat, Dextrosa 5% dalam NaCl 0,45%, Dextrosa 5% dalam larutan garam atau NaCl 0,9%.
Jumlah cairan yang diberikan dengan perkiraan selama 24 jam, pasien mengalami dehidrasi sedang, maka pasien dengan berat badan sekitar 50-70 kg diberikan Ringer Laktat perinfus sebanyak 3.000 cc/24 jam. Pada pasien dengan berat badan lebih dari 70 kg dapat diberikan cairan infus sampai dengan 4.000 cc/24 jam. Jumlah ini harus diperhitungkan kembali dengan cermat terutama pada usia kehamilan 28-32 minggu.
Selama fase akut jumlah cairan infus diberikan pada hari berikutnya setiap harinya tetap sama dan pada saat mulai didapatkan tanda-tanda penyembuhan yaitu suhu tubuh mulai menurun, pasien dapat minum dalam jumlah cukup banyak (sekitar 2 liter/24 jam) dan tidak didapatkan tanda-tanda hemokonsentrasi serta jumlah trombosit mulai meningkat lebih dari 50.000/ul, maka jumlah cairan infus selanjutnya dapat mulai dikurangi.
Mengingat jumlah pemberian cairan infus pada pasien DBD dewasa tanpa perdarahan masif dan tanpa syok tersebut sudah memadai, maka pemeriksaan Hb, Ht, dan trombosit dilakukan setiap 12 jam untuk pasien dengan jumlah trombosit kurang dari 100.000/ul, sedangkan untuk pasien dengan jumlah trombosit berkisar 100.000-150.000/ul, pemeriksaan dilakukan setiap 24 jam. Pemeriksaan darah, frekuensi nadi dan pernafasan, dan jumlah urin dilakukan setiap 6 jam, kecuali bila keadaan pasien makin memburuk dengan didapatkannya tanda-tanda syok, maka pemeriksaan tanda-tana vital harus diawasi dengan ketat.
Mengenai tanda-tanda syok harus diwaspadai sedini mungkin karena penatalaksanaan pasien dengan syok (DSS) lebih sulit, dan disertai dengan risiko kematian yang lebih tinggi. Tanda-tanda syok dini yang harus segera dicurigai adalah apabila pasien tampak gelisah, atau adanya penurunan kesadaran, akral teraba dingin dan tampak pucat, serta jumlah urin yang menurun kurang dari 0,5 ml.kgBB/jam. Gejala-gejala tersebut merupakan tanda berkurangnya aliran darah ke organ vital tubuh. Tanda-tanda lain syok dini adalah tekanan darah menurun dengan tekanan sistolik kurang dari 100 mmHg, tekanan nadi kurang dari 20 mmHg, nadi cepat dan kecil. Apabila ditemui tanda-tanda tersebut, maka penatalaksanaan DBD dengan syok (DSS) harus segera diberikan.
Transfusi trombosit hanya diberikan pada DBD dengan perdarahan masif (perdarahan dengan jumlah darah 4-5 ml/kgBB/jam) dengan jumlah trombosit < 100.000 ul, dengan atau tanpa koagulasi intravaskular diseminata (KID). Pasien DBD dengan trombositopenia tanpa perdarahan masif tidak diberikan transfusi suspensi trombosit.
Pasien dapat dipulangkan apabila:
a. Keadaan umum/kesadaran dan hemodinamika baik, serta tidak demam
b. Pada umum Hb, Ht dan jumlah trombosit dalam batas normal serta stabil 24 jam, tetapi dalam beberapa keadaan, walaupun jumlah trombosit belum mencapai normal, pasien sudah dapat dipulangkan.
2. Penatalaksanaan DBD dengan perdarahan spontan dan masif tanpa syok
Perdarahan spontan dan masif pada pasien DBD misalnya epistaksis, perdarahan saluran cerna (hematemesis dan melena atau hematoskesia), perdarahan saluran kencing (hematuria), perdarahan otak dan perdarahan tersembunyi, dengan jumlah perdarahan sebanyak 4-5 ml/kgBB/jam. Pada keadaan seperti ini jumlah dan kecepatan pemberian cairan Ringer Laktat tetap seperti keadaan DBD tanpa renjatan lainnya yaitu 500 ml/4 jam. Pemeriksaan tekanan darah, nadi, pernafasan, dan jumlah urin dilakukan sesering mungkin dengan kewaspadaan terhadap tanda-tanda syok sedini mungkin. Pemeriksaan Hb. Ht dan trombosit sebaiknya diulang setiap 4-6 jam.
Heparin diberikan apabila secara klinis dan laboratoris didapatkan tanda-tanda KID. Transfusi komponen darah diberikan sesuai indikasi. Fresh Frozen Plasma diberikan bila didapatkan defisiensi faktor-faktor pembekuan (PT dan PTT yang memanjang). Packed Red Cell (PRC) diberikan bila nilai Hb kurang dari 10 g%. Transfusi trombosit hanya diberikan pada DBD dengan perdarahan spontan yang masif dengan jumlah trombosit kurang dari 100.000 µl, disertai dengan KID.
3. Penatalaksanaan DBD dengan syok dan perdarahan spontan
Pada kasus DBD dengan syok (DSS), cairan yang diberikan adalah Ringer Laktat sebagai cairan kristaloid pertama karena mengandung Na laktat sebagai korektor basa. Pilihan lainnya adalah NaCL 0,9%. Selain resusitasi cairan, pasien juga diberi oksigen 2-4 liter/menit, dan pemeriksaan yang harus dilakukan adalah pemeriksaan darah perifer lengkap, pemeriksaan hemostasis, analisis gas darah, kadar elektrolit natrium, kalium, klorida, serta ureum dan kreatinin.
Pada fase awal Ringer Laktat diberikan sebanyak 20 ml.kgBB/jam dan kemudian dievaluasi selama 30-120 menit. Syok harus dapat diatasi segera dalam 30 menit pertama. Syok dinyatakan teratasi bila keadaan umum pasien membaik, kesadaran/keadaan sistem saraf pusat baik, tekanan sistolik 100 mmHg atau lebih dengan tekanan nadi lebih dari 20 mmHg, frekuensi nadi kurang dari 100/menit dengan volume yang cukup, akral teraba hangat dan kulit tidak pucat, serta diuresis 0,5-1 ml/kgBB/jam.
Apabila syok sudah dapat diatasi, pemberian Ringer Laktat selanjutnya dapat dikurangi menjadi 10 ml/kgBB/jam dan dievaluasi selama 60-120 menit berikutnya. Bila keadaan klinis stabil, maka pemberian cairan Ringer Laktat selanjutnya sebanyak 500 cc/4 jam. Pengawasan dini terhadap kemungkinan terjadinya syok berulang harus dilakukan terutama dalam waktu 48 jam pertama sejak terjadinya syok, oleh karena selain proses patogenesis penyakit masih berlangsung, juga karena sifat cairan kristaloid hanya sekitar 20% saja yang menetap dalam pembuluh darah setelah 1 jam dari saat pemberiannya. Oleh karena itu apabila hemodinamik masih belum stabil dengan nilai Ht lebih dari 30 vol%, dianjurkan untuk memakai kombinasi kristaloid dan koloid dengan perbandingan 4:1 atau 3:1, sedangkan bila nilai Ht kurang dari 30 vol% hendaknya diberikan transfusi sel darah merah (PRC).
Pemberian antibiotik perlu dipertimbangkan pada DBD dengan syok mengingat kemungkinan infeksi sekunder dengan adanya translokasi bakteri dari saluran cerna. Indikasi lain pemakaian antibiotik pada DBD adalah apabila didapatkan adanya infeksi sekunder di tempat lain. Antibiotik yang digunakan hendaknya tidak mempunyai efek terhadap sistem pembekuan.
Penatalaksanaan DBD dengan syok tanpa perdarahan
Pada prinsipnya penatalaksanaan kelompok ini mirip dengan penatalaksanaan pasien DBD dengan syok dan perdarahan, hanya pemeriksaan secara klinis maupun laboratorium perlu dilakukan secara lebih teliti dan seksama untuk menentukan kemungkinan adanya perdarahan yang tersembunyi disertai dengan KID. Apabila tidak ditemukan tanda-tanda perdarahan, walaupun hasil hemostasis menunjukkan adanya KID, heparin tidak diberikan, kecuali bila ada perkembangan ke arah perdarahan.
DAFTAR PUSTAKA
1. Dengue Haemorrhagic Fever. Diakses dari: http://www.who.int/csr/resources/publications/dengue/012-23.pdf
2. Hadinagoro SR. Tatalaksana Demam Dengue/Demam Berdarah dengue. Departemen Kesehatan Republik Indonesia Rektorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular Dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman. 1999
3. Satari HI. Demam Berdarah Dengue. Naskah Lengkap Pelatihan Bagi Dokter Spesialis Anak dan Dokter Spesialis Penyakit Dalam dalam Tatalaksana Kasus DBD. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Indonesia. Jakarta, 1999
4. Prawirohardjo S. Penyakit Menular. Ilmu Kebidanan. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. Jakarta, 1999: 567-560
5. Sumarmo S.P.S. Infeksi Virus Dengue. Buku Ajar Infeksi dan Penyakit Tropis. Hipokrates. Jakarta, 1999: 177-205
6. Prasetyo AA. Infeksi Virus Dengue. Infeksi Virus & Kehamilan. Penerbit Pustaka Cakra Surakarta. Surakarta, 2005: 138-142
7. WHO. Reported Cases and Deaths of DF/DHF in SEAR. Diakses dari http://www.who.int
8. Hacker NF, Moore JG. Fisiologi Ibu. Esensial obstetri dan ginekologi. Jakarta : Hipokrates, 2001 : 68-82
9. Cunningham FG, Gant NF, Leveno KJ. Anatomy and Physiology. William Obstetrics, 22nd ed. Mc Graw Hill Medical Publishing Division. New York, 2001: 64-66
10. Prawirohardjo S. Perubahan Anatomik dan Fisiologik pada Wanita Hamil. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. Jakarta, 1999: 89-100
11. Soegijanto Soegeng. Aspek Imunologi Penyakit Demam Berdarah Dengue. Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Surabaya, 1998: 11-33
12. Dengue Fever. Diakses dari: http://www.acpmedicine.com/sample2/ch0731s.htm
13. Shepherd Suzanne. Dengue Fever. Diakses dari: http://www.emedicine.com/MED/topic528.htm
14. Acang Nusirwan. Pemberian Cairan Pada Demam Berdarah Dengue. Bagian Ilmu Penyakit Dalam FK-Unand. RS Dr. M. Djamil Padang
15. Dengue Type 1 Epidemic in Polynesia 2001. Diakses dari: http://www.spc.org.nc/phs/PPHSN/Outbreak/Reports/Dengue_report2001-FrenchPolynesia.pdf
16. Saibi DA. Demam Berdarah Dengue Pada Kehamilan, Persalinan dan Nifas. Bagian Obstetri dan Ginekologi RSCM FKUI. Jakarta, 1998
17. Dengue Fever. Disease Control and Prevention. Public Health Notifiable Disease Management Guidelines December 2005. Diakses dari: http://www.health.gov.ab.ca/professionals/ND_DengueFever.pdf
18. Dengue Hemorrhagic Fever. Diakses dari: http://www.shands.org/health/information/article/001373.htm