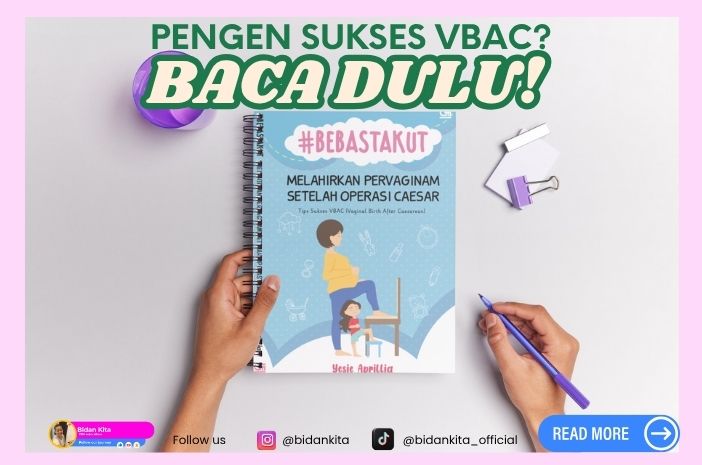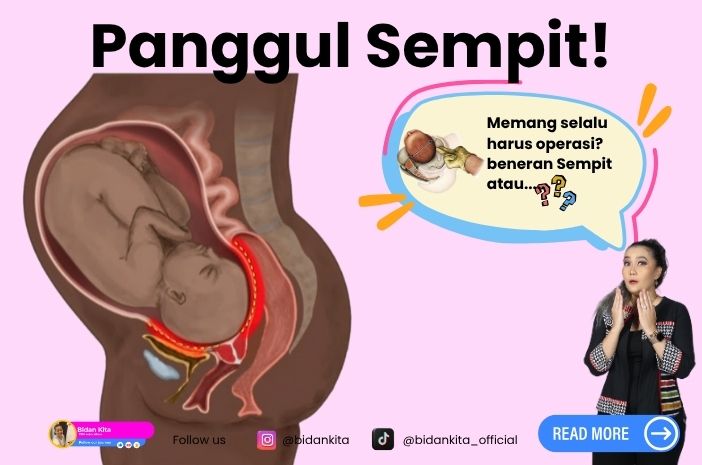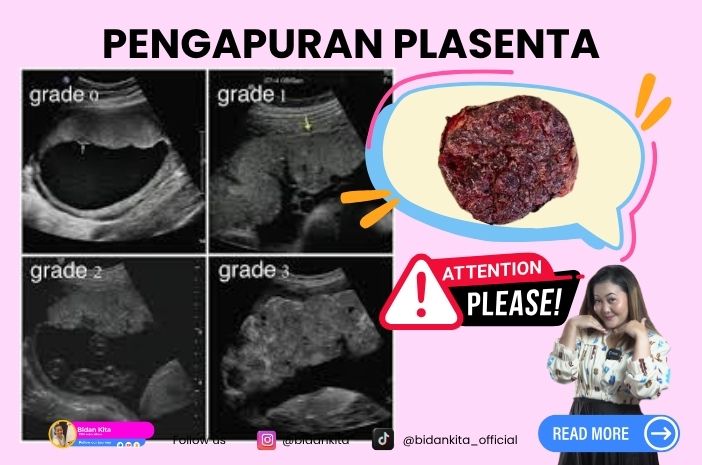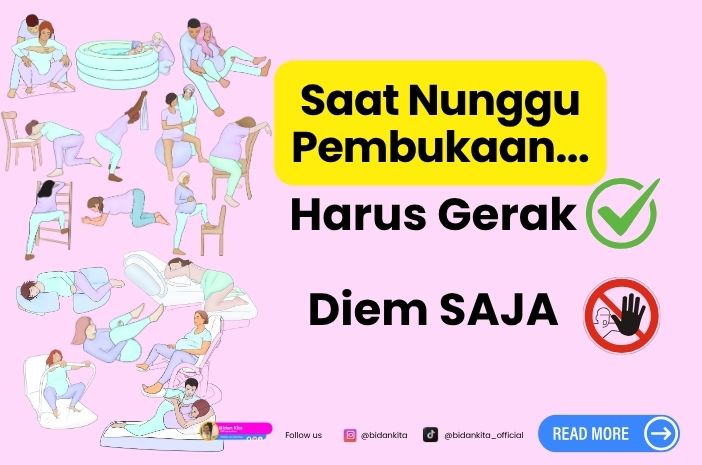Takut Perineum Robek Saat Lahiran? Ini yang Wajib Ibu Tahu dari Awal!
“Aku takut robek, Bid… Katanya robekan perineum itu sakit banget dan bisa sampai dijahit OBRAS.” Kalimat ini sudah sering sekali kami dengar di kelas-kelas persiapan persalinan. Dan memang benar—ketakutan soal robekan perineum adalah keresahan umum banyak ibu menjelang persalinan. Beberapa ibu bahkan datang ke kelas sambil menggenggam tangan suaminya erat-erat, lalu berbisik, “Bidan, aku tuh…